Anggur Salak Rasa Tapai Ketan: Menikmati Kelezatan Bali yang Menyegarkan
.jpg)
Pernahkah Anda berkunjung ke sentra penanaman salak di Desa Telagae, Karangasem, Bali? Jika iya, cobalah untuk mampir ke toko-toko penjaja oleh-oleh setempat. Di sana, Anda akan menemukan botol-botol transparan berisi larutan bening yang menarik perhatian. Namun, bagi Anda yang tidak minum alkohol, sebaiknya berhati-hati, karena itu adalah anggur hasil fermentasi dari buah salak Bali.
.jpg) Tapi, bagi yang penasaran ingin mencicipi, jangan khawatir, karena rasanya seperti tapai ketan yang nikmat, begitu tutur I Wayan Putu Ardika, ketua Kelompok Tani Mekarsari, anggota Kelompok Usaha Bersama Lestari yang merupakan salah satu penghasil wine asal buah Salacca zalacca.
Tapi, bagi yang penasaran ingin mencicipi, jangan khawatir, karena rasanya seperti tapai ketan yang nikmat, begitu tutur I Wayan Putu Ardika, ketua Kelompok Tani Mekarsari, anggota Kelompok Usaha Bersama Lestari yang merupakan salah satu penghasil wine asal buah Salacca zalacca.
Proses pembuatan anggur salak ini menggunakan bahan baku berupa buah salak yang tidak laku dijual segar karena ukurannya terlalu kecil atau kulitnya cacat. Buah salak ini banyak dimanfaatkan dari berbagai varietas lokal seperti salak nangka, salak nanas, dan salak getih (yang dalam bahasa Bali berarti darah), semuanya dikenal sebagai salak Bali.
Setelah dipisahkan dagingnya dari kulit dan biji, buah salak tersebut kemudian diparut dan diperas. Air perasan dari buah salak ini kemudian difermentasi sehingga menghasilkan kandungan alkohol yang memberikan rasa unik pada anggur salak Bali ini. Sebelum dikemas dalam botol-botol transparan, anggur salak ini diolah agar tampak bening, dan itulah yang dijajakan di toko-toko sekitar Karangasem.
Ternyata, buah salak ini juga sering diolah menjadi berbagai jenis makanan lezat seperti asinan atau manisan, yang menjadi favorit para perajin di Sukabumi atau Cianjur. Selain itu, ada juga permen salak yang dihasilkan dari daerah Sibetan, Karangasem, yang memiliki cita rasa yang tak kalah enak. Bahkan kini, salak mulai dikalengkan, yang membuat tampilannya menjadi lebih eksklusif. Namun, meskipun telah diolah menjadi berbagai hidangan lezat, pemanfaatan buah salak sebagai buah segar tetap menjadi yang utama.
Di Yogyakarta, ada salah satu varietas salak yang terkenal, yaitu salak pondoh. Meskipun ukuran buahnya relatif kecil dibandingkan dengan varietas lain, seperti salak super dari Desa Blitar, Banjarnegara, Jawa Tengah, rasanya tidak kalah manis dan lezat. Keunggulan dari salak pondoh adalah buahnya berdaging putih seperti pucuk kelapa yang masih terbungkus pelepahnya (dalam bahasa Jawa disebut pondoh). Kualitas buah salak yang baik di tingkat pekebun dijual dengan harga Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram, namun ketika sampai di tangan konsumen lokal harganya naik menjadi Rp8.000, dan jika dijual di luar kota seperti Jakarta, harganya mencapai Rp12.000 per kilogram.
Salak pondoh ini bahkan memiliki potensi yang besar sehingga dikembangkan di luar sentra penanamannya. Sejak lima tahun silam, salak pondoh sudah ditanam seluas 20 hektar di wilayah Sumatera Selatan. Ini menunjukkan betapa pentingnya buah salak ini bagi masyarakat Indonesia, bahkan sejak zaman Belanda dulu.
Dalam sejarahnya, salak pondoh mendapatkan perhatian khusus dari seorang pria Belanda yang berbaik hati, yang meninggalkan kenang-kenangan empat pot salak untuk Partomejo, kepala desa Merdikareja, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, sebelum pulang ke Belanda pada tahun 1917. Bibit salak tersebut kemudian diperbanyak dan menyebar ke berbagai daerah di Indonesia, seperti Semarang, Wonosobo, Boyolali, hingga Lampung. Selama ini, buah salak ini menjadi salah satu buah favorit masyarakat Indonesia.
Kehadiran buah salak juga membawa berkah tersendiri bagi beberapa daerah, seperti di Sibetan, Bali, yang menjadi sentra penanaman salak terbesar di pulau Dewata. Hal ini membuat Sibetan menjadi populer di seluruh negeri, karena menjadi tempat wisata agro yang menarik bagi para turis. Masyarakat Sibetan merayakan Tumpek Pengatang atau Tumpuk Uduh sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang subur. Upacara ini diisi dengan berbagai pertunjukan seni dan tarian tradisional seperti tari topeng, rejang, dan pendet yang dipadukan dengan musik gamelan. Wisata agro ini juga menawarkan kesempatan bagi para pengunjung untuk memetik sendiri buah salak pondoh yang segar langsung dari kebunnya, sebuah pengalaman yang tak terlupakan.
Selain menjadi makanan yang lezat, salak juga memiliki potensi ekonomi yang besar bagi Indonesia. Produksi salak Indonesia sebagian besar tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen lokal, tetapi juga diekspor ke beberapa negara seperti Belanda dan Arab Saudi. Kelezatan buah salak yang cocok hampir di lidah setiap orang membuatnya menjadi primadona di pasaran. Banyak petani yang tertarik untuk menanam salak karena teknis penanamannya tidak terlalu sulit. Salak tumbuh subur di daerah dengan ketinggian antara 200 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Tanah bekas tumpukan debu vulkanik seperti lereng Gunung Merapi, kaki Gunung Galunggung, dan Gunung Agung menjadi lokasi penanaman yang menghasilkan kualitas buah salak yang lebih baik.
Tidak hanya itu, salak juga menjadi komoditas ekspor bagi negara-negara tetangga Indonesia, seperti Malaysia dan Thailand. Di Malaysia, salak dengan daging tebal dan kaya air menjadi favorit masyarakat. Sementara di Thailand, salak berbentuk kurus dan lonjong dengan daging merah yang asam menjadi penyedap masakan yang lezat. Di Indonesia sendiri, terdapat beragam jenis salak lokal unggulan dari berbagai daerah, seperti salak hijau dari Bangka Belitung, salak padang sidempuan dari Sumatera Utara, salak magnified, salak dranfieldiana, dan salak vermiculata dari Kalimantan, serta berbagai jenis salak lainnya dari berbagai daerah di Indonesia.
Selain memiliki kelezatan yang unik, salak juga memiliki nilai historis dan kultural yang penting bagi masyarakat Indonesia. Di tengah beragam jenis buah tropis yang ada di Indonesia, salak tetap menjadi buah yang spesial dengan nilai ekonomi dan kearifan lokal yang tinggi. Keberadaan salak pondoh di lereng Gunung Merapi, yang menjadi salah satu sentra penanaman salak terbesar di Yogyakarta, menunjukkan betapa salak tetap menjadi buah yang sangat berarti bagi masyarakat Indonesia.
Dalam rangka meningkatkan potensi ekonomi dan wisata agro dari buah salak ini, pemerintah dan masyarakat setempat perlu melakukan berbagai upaya, seperti peningkatan teknis penanaman, pengembangan pasar, dan promosi wisata agro yang menarik. Selain itu, kualitas buah salak yang baik juga harus tetap dijaga, agar dapat memenuhi permintaan pasar lokal maupun internasional. Dengan potensi yang besar dan kelezatan yang khas, salak berpeluang menjadi salah satu komoditas unggulan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia.
Demikianlah penulisan ulang mengenai anggur salak rasa tapai ketan dari Bali. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang tertarik dalam topik ini. Jangan lupa untuk berbagi artikel ini dengan orang lain agar lebih banyak orang yang mengetahui tentang kelezatan buah salak dan potensinya bagi perekonomian Indonesia.
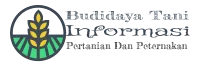 Never miss a story from us, subscribe to our newsletter
Never miss a story from us, subscribe to our newsletter